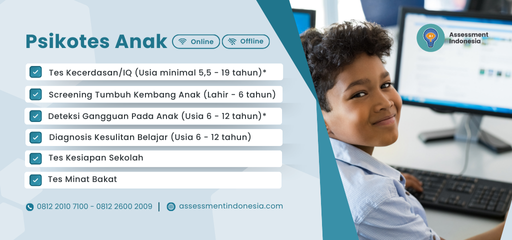Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kita membuka Instagram saat bangun tidur, mengecek Twitter untuk berita terkini, menonton video di TikTok untuk hiburan, dan menggunakan WhatsApp atau Telegram untuk menjaga koneksi sosial. Namun, di balik kemudahan ini, muncul pertanyaan penting: apakah media sosial benar-benar membantu dalam mendukung kesehatan mental, khususnya dalam konteks Mental Health First Aid (MHFA), atau justru menjadi sumber tekanan yang memperparah kondisi psikologis seseorang?
Dalam konteks MHFA, media sosial sering digambarkan sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ia memiliki kekuatan luar biasa untuk menyebarkan informasi, membuka ruang diskusi, dan menghubungkan orang-orang yang sebelumnya merasa sendiri dalam perjuangan mental mereka. Kampanye-kampanye seperti #MentalHealthAwareness, #ItsOkayToNotBeOkay, atau #TalkAboutIt telah menjadi gerakan global yang membuat isu kesehatan mental lebih terbuka dibicarakan. Banyak orang merasa lebih mudah berbagi cerita melalui teks atau video pendek daripada bicara langsung. Media sosial, dalam hal ini, menjadi jembatan awal untuk mengenali, merespons, atau bahkan meminta bantuan saat seseorang mengalami krisis psikologis.
Tidak sedikit pula akun-akun yang secara khusus membagikan konten edukasi seputar MHFA, mulai dari tanda-tanda depresi, cara merespons orang yang mengalami serangan panik, hingga tips mendengarkan tanpa menghakimi. Keberadaan konten semacam ini membantu masyarakat memahami bahwa mereka bisa menjadi penolong awal, bahkan tanpa latar belakang profesional di bidang kesehatan mental. Lebih dari itu, media sosial juga menyediakan ruang untuk peer support, di mana individu yang mengalami pengalaman serupa bisa saling menguatkan. Banyak orang menemukan komunitas daring yang menjadi tempat aman mereka saat dunia nyata terasa asing.
Namun, di sisi lain, media sosial juga memiliki sisi gelap yang seringkali luput disadari. Algoritma yang bekerja berdasarkan interaksi emosional membuat konten tentang kesehatan mental yang dramatis atau ekstrem justru lebih cepat viral. Tidak semua informasi yang beredar benar atau bertanggung jawab. Beberapa akun bahkan menyederhanakan diagnosis atau memberikan saran tanpa landasan ilmiah, sehingga memunculkan fenomena self-diagnosis yang bisa berbahaya. Seseorang mungkin membaca satu utas tentang ADHD dan langsung merasa memiliki gangguan tersebut, tanpa melalui proses evaluasi profesional. Dalam konteks MHFA, informasi yang salah dapat memperburuk kondisi, baik bagi yang memberi bantuan maupun yang menerimanya.
Selain itu, tekanan sosial di media juga bisa memperburuk kesehatan mental individu. Fenomena toxic positivity, di mana semua hal harus tampak baik, penuh syukur, dan bahagia membuat seseorang merasa bersalah karena sedang merasa buruk. Alih-alih mendapat dukungan, seseorang yang sedang depresi bisa merasa lebih terisolasi karena merasa berbeda dari narasi kebahagiaan kolektif yang ditampilkan di linimasa. Tidak sedikit juga yang merasa terjebak dalam budaya membandingkan diri, sehingga harga diri terganggu. Dalam banyak kasus, ini menciptakan “krisis senyap” yang tidak terlihat, tapi berdampak besar secara psikologis.
Dari sisi relasi, media sosial pun dapat menciptakan ilusi koneksi. Komentar “semangat ya!” atau “aku selalu di sini kalau butuh cerita” seringkali terasa dangkal ketika tidak diiringi dengan aksi nyata. Dalam MHFA, kehadiran emosional dan empati langsung sangat penting. Sayangnya, interaksi di media sosial cenderung cepat, dangkal, dan sulit untuk menggantikan kualitas pertemuan tatap muka atau percakapan bermakna. Ini menjadi tantangan besar ketika seseorang mencoba menerapkan prinsip MHFA hanya lewat layar: niat baik bisa salah paham, atau bahkan memicu respons yang tidak diinginkan.
Meski begitu, bukan berarti media sosial sepenuhnya buruk dalam konteks MHFA. Yang dibutuhkan adalah literasi digital dan literasi emosi yang baik. Kita perlu tahu bagaimana memilah informasi, mengenali batas diri saat merasa jenuh terhadap konten-konten emosional, dan memahami bahwa tidak semua bantuan bisa diberikan secara daring. Salah satu cara untuk tetap sehat secara mental di media sosial adalah dengan mengatur kurasi konten: ikuti akun-akun yang edukatif dan suportif, batasi waktu penggunaan, serta aktif membangun komunitas yang benar-benar saling peduli.
Penting juga untuk mengingatkan diri sendiri bahwa membantu orang lain melalui media sosial, seperti membalas curhatan atau membagikan konten edukatif, tidak serta-merta membuat kita bertanggung jawab penuh atas kondisi mereka. Dalam MHFA, batas peran adalah hal yang penting. Kita bisa menjadi jembatan yang mengarahkan seseorang ke bantuan profesional, tapi kita tidak harus menjadi “penyembuh” utama. Kesadaran ini penting agar tidak timbul rasa frustrasi atau kelelahan emosional yang berlebihan, terutama bagi orang yang sering menjadi tempat curhat banyak orang secara daring.
Pada akhirnya, peran media sosial dalam MHFA sangat bergantung pada cara kita menggunakannya. Ia bisa menjadi alat yang memperluas dampak kebaikan dan edukasi, tapi juga bisa menjadi sumber tekanan jika digunakan tanpa kesadaran. Dalam masyarakat yang semakin terdigitalisasi, kemampuan untuk tetap hadir secara empatik, menjaga batas, dan terus belajar menjadi kunci utama untuk menjadikan media sosial sebagai ruang yang benar-benar mendukung kesehatan mental bersama. Temukan layanan asesmen psikologi terbaik hanya di biro psikologi resmi Assessment Indonesia, mitra terpercaya untuk kebutuhan psikotes.
Referensi:
Naslund, J. A., Aschbrenner, K. A., Marsch, L. A., & Bartels, S. J. (2016). The future of mental health care: Peer-to-peer support and social media. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 25(2), 113–122.
American Psychological Association. (2020). Social Media and Mental Health. https://www.apa.org
World Health Organization. (2022). Digital mental health: Challenges and opportunities. https://www.who.int